Setakat ini saya belum menemukan huraian mengenai syurga dan neraka yang cukup berkesan dan mudah difahami oleh ulama-ulama tempatan. Kebanyakannya saya dengar hanyalah berkisar kepada suasana ‘syurga yang dijanjikan’ dan apa yang perlu (umat Islam) lakukan untuk ke sana. Pemahaman secara falsafah tidak dikupas dengan baik, hanya sepintas lalu dan sangat tidak memberikan motivasi, sebagaimana ulama-ulama terdahulu mengupasnya.
Bagi saya, ia adalah satu kelemahan dan kegagalan ustaz-ustaz segera dalam hal ini, kecuali boleh berceramah dengan cukup menarik mengenai ‘poligami’. Sebab itulah bila terungkapnya istilah ‘syurga yang dijanjikan’ ramai pula merujuk kepada kisah cinta dan poligami bahkan ada yang berkempen, rebutlah ‘payung emas’.
Hal ini mengingatkan kita seolah-olah kehidupan masyarakat Islam penuh dengan cerita poligami, dan ia menjadi bukti yang sangat kelihatan jelas apabila ramai ustaz-ustaz mengamalkannya atas kedudukan hukumnya. Apa yang tidak diberikan penekanan ialah bagaimana poligami itu diberikan kebenaran dan apa yang menjadi pendorongnya.
Atas kegagalan itulah ramai wanita menentang dan tidak bersetuju (amalan poligami), sehingga timbul pula situasi yang cukup paradoks. Hal ini berlaku kerana kegagalan ustaz-ustaz dan ustazah memberikan pendidikan terhadap keperluan poligami, dan membiarkan wanita dipengaruhi oleh aliran feminisme dan liberalisme barat.
Barat menentang poligami, tetapi boleh menghalalkan bersekedudukan (tanpa perkahwinan), perkahwinan sejenis dan melakukan perbuatan zina. Bagi masyarakat barat, semuanya boleh berlaku sekiranya tidak ada unsur paksaan. Ia adalah atas kerelaan masing-masing, tetapi ironinya, seorang isteri akan memfailkan penceraian bila suaminya ada kekasih gelap. Misalnya, kisah penceraian Bill dan Melinda Gates yang sedang hangat diperkatakan.
Sebaliknya, pasangan yang bersekedudukan tidak pula dilihat sebagai kesalahan (dosa sosial), sebabnya, agama sudah diketepikan dalam kerangka hidup keseharian. Begitu juga dengan kelahiran ‘anak luar nikah’; ia sah taraf walaupun dilahirkan oleh pasangan bersekedudukan.
Dari satu perspektif, penerimaan ‘anak luar nikah’ adalah satu hal yang menarik, terutama dari pandangan kemanusiaan. Kesalahan bukan kerana anak itu lahir secara ‘anak luar nikah’, maka ia tidak wajar dipersalahkan, pasangan bersekedudukan juga tidak salah kerana moral yang diterima ialah atas asas kesukarelaan. Kesukarelaan itulah sebahagian daripada prinsip hak asasi dan kebebasan. Disebabkan agama adalah bersifat peribadi, maka ia sepatutnya dikaitkan dengan kesalahan bersekedudukan, dan penzinaan.
Hubungan seks bukan lagi sesuatu yang salah atau berdosa sekiranya berlaku atas kerelaan masing-masing. Itulah yang menjadikan negara-negara barat juara dalam kelahiran anak luar nikah, aktiviti hiburan yang sangat berkait rapat dengan persundalan, dan industri erotik.
Bersekedudukan telah diterima sebagai pola kehidupan lazim, dan sangat bernormal, ia bukan ‘dosa sosial’, juga dosa agama. Bagi mereka, agama bukan lagi penentu atau kerangka cara hidup, hanya sekadar kepercayaan, satu kaedah pengisian jiwa yang hanya berteraskan kutipan ungkapan dan kata-kata.
Seperti dijelaskan oleh William James (1842-1910) sebagai “diri yang terbelah” – dunia adalah sebuah misteri dua sisi: kehidupan spiritual dan kehidupan alami di mana salah satunya ‘harus ditinggalkan’ sebelum ikut dalam kehidupan lainnya. Ia akhirnya membentuk ‘semacam pertentangan (discordancy), suatu ‘perwatakan moral serta intelektual yang menyatu secara kurang lengkap”. (William James, Perjumpaan Dengan Tuhan: Ragam Pengalaman Religius Manusia, edisi terjemahan, 2004, hal.254-255)
Islam tidak menerima kededuanya, tetapi tidak sampai kepada peringkat membunuh ‘anak luar nikah’ yang tidak berdosa meskipun ada kecenderungan menghalau atau menyisihkan ahli keluarga yang hamil tanpa nikah. Ertinya, tidak ada sokongan sosial yang cukup untuk membantu, walaupun dari perspektif institusi ada pihak yang sedia menjaga dan menghulurkan bantuan.
Apa yang lebih penting ialah bagaimana sikap dan pendirian tokoh-tokoh agama berhubung dengan masalah itu. Apakah cukup dengan kenyataan-kenyataan yang menggerunkan? Tetapi, bagaimana untuk membantu dan apa mekanisme untuk mencegahnya? Bukan sekadar, kembali kepada pendidikan agama? Pendidikan agama bagaimana dan apa bentuknya?
Belum ada kerangka, kecualilah sekadar meletakkan anak-anak di sekolah tahfiz atau pondok dengan harapan anak-anak tidak ‘nakal’ dan ‘salah kiprah’. Masih tidak dapat membantu, kerana syurga yang diharapkan, tetapi kehidupan dan persekitaran tidak dibangunkan dengan sistem ‘membangun syurga’.
Itulah kesimpulan yang saya dapat daripada kecerdasan Achmad Chodjim menyarankan, bentuk dulu syurga di dunia, yang aman, damai dan harmoni, bukan hanya sekadar berharap syurga di akhirat. Bagaimana nak merasakan syurga di akhirat sekiranya hidup di dunia saling berkelahi, tidak saling memaafkan, berdendam dan adu domba, keluarga berantakan (penceraian meningkat), orang tua hidup dalam kesepian (tanpa anak-anak), individualistik, berlumba-lumba untuk mendapatkan kuasa, rasuah, salah guna kuasa, bunuh-membunuh (fizikal dan pembunuhan karakter), seumpama adegan-adegan yang cukup bermasalah dalam drama rantaian.
Apakah umat Islam sudah jauh terpesong dan para ulama tidak lagi memahami makna ‘kasih sayang’? Kasih itu bukan hanya berlangsung dalam kalangan ahli keluarga, ia meluas ke dalam kehidupan berjiran dan bermasyarakat. Apakah kita sedar bahawa ada jiran sebelah yang kesempitan hidupnya kerana hilang pekerjaan atau dilanda musibah? Berapa kerapkah kita bertanya khabar, menjengok dan membantu mereka?
Apa yang berlaku, bila ada pihak luar menghulurkan bantuan, muncul pula pemimpin tempatan bertindak sebagai ‘algojo’ dan menafikan bahawa ‘kami tidak membantu’. Atau komen Timbalan Menteri Besar Kelantan, “kebaikan tidak berakal akan mencetuskan fitnah berangkai.” Kita juga mungkin belum terlupa, bila seorang pegawai di Pejabat Menteri Besar Kedah mengeluarkan kenyataan, “bagi sumbangan tak tanya kami” dan “jahatkah kami”?. Sepatutnya kontroversi dan kejengkelan begitu tidak timbul.
Timbuskan perbezaan, perbanyakkan persamaan, maka hidup akan benar-benar aman. Tidak ada pertentangan, dan yang susah akan menjadi lebih mudah dalam merungkaikan penyelesaian secara ikhlas, jujur dan sedar kedudukan diri hanyalah sebagai hamba, bukan tuan. Tuan yang sebenar, manusia, makhluk dan apa yang ada di bumi ialah Allah SWT, maka, setiap fikiran, tindakan dan jalan yang kita tempohi seharian ialah mendapatkan keredhaan-Nya, bukan seperti ulama atau agamawan yang cenderung menasihati orang lain tetapi diri sendiri terperangkap dengan keindahan dunia dan jauh daripada zuhud.
BACA JUGA: AGAMAWAN DAN ‘BAKUL SAMPAH AGAMA’, https://omiw.com.my/Web/2021/06/16/agamawan-dan-bakul-sampah-agama/
BACA JUGA: AGAMAWAN DAN ‘BAKUL SAMPAH AGAMA (II), https://omiw.com.my/Web/2021/06/19/agamawan-dan-bakul-sampah-agama-ii/
BACA JUGA: AGAMAWAN DAN ‘BAKUL SAMPAH AGAMA (III), https://omiw.com.my/Web/2021/06/20/ulama-dan-bakul-sampah-agama-iii/
Meskipun Jalaludin Rumi lebih terkenal dengan Mastnawi, kumpulan ceramah spiritualnya juga cukup menarik untuk diteladani bagi menghindar diri daripada ‘kejahatan dan kenakalan psikologi manusia’, termasuk oleh para yang bergelar pemimpin, iman ataupun politikus dan agamawan. Nasihat-nasihatnya mampu melahir rasa bersalah atau membuka ruang taubat (keinsafan). Di sisi Allah SWT, keinginan seseorang yang menyesal di atas ‘kejahatan dan kenakalan’ itulah sangat diterima untuk dikategorikan sebagai ‘penghuni syurga’.
Orang bertaubat, tidak akan mengulangi ‘kejahatan dan kenakalan’ yang sudah ditolaknya. Dia akan terus menempatkan diri untuk dilahirkan sebagai orang yang baik, sama ada mempertingkatkan takwa atau hamba Allah berlandaskan amar makruf, menyeimbangkan pula perilaku untuk membahagiakan orang lain, senyum dalam kesusahan (sabar menerima ujian), syukur bila memperoleh sesuatu dan berbuat baik dengan ahli keluarga, sahabat, jiran dan sesiapa sahaja tanpa rasa jelek dan sombong.
Ada sebuah anekdot dari satu cerita sufi. Dikatakan, seorang pelacur diterima sebagai penghuni syurga hanya kerana menceduk air dengan kasut untuk diberikan minum kepada seekor anjing yang hampir mati kehausan. Satu lagi anekdot sufi, seorang pakar bahasa menolak pertolongan seorang darwis hanya kerana kalimat dan perucapannya tidak menepati pola bahasa. Ahli bahasa itu akhirnya bermalam dalam kegelapan setelah terjatuh di dalam perigi kerana ujub dengan kepakarannya, dan meremehkan tawaran pertolongan oleh seorang darwis.
Ertinya, perbezaan pendapat, persepsi sentiasa berlaku, tetapi perbezaan-perbezaan itu tidak sepatutnya dijadikan pemisah. Seharusnya, perbezaan itu diterima dan dijadikan pengajaran seperti mana Allah SWT menyuruh ‘saling berkenal-kenalan’ dan hidup dengan harmoni. Jauhkan sengketa, bukan memperbesarkan perbezaan.
Apa yang berlaku dalam masyarakat, kerana perbezaan di peringkat ranting (furudiyyah) bukan bermakna “kafir”, seperti tidak berketayap putih ke majlis agama. Ketayap putih bukan perkara yang wajib, dan bukan juga ada nas yang boleh dikaitkan sebagai sunat, makruh ataupun haram. Ia hanyalah suatu peristiwa budaya, kalau dipakai dilihat sopan dan santun. Itu sahaja.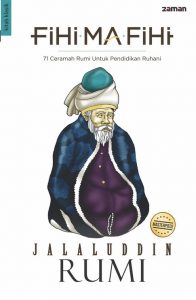
Ketika manusia melihat orang lain dengan perspektif berbeza, Jalaludin Rumi cukup tegas memberikan pandangannya. Semua sifat baik dan buruk ada dalam diri setiap manusia, tetapi bila seseorang itu berhadapan dengan orang lain, semua “sifat-sifat buruk – zalim, iri, dengki, srakah, keras hati, dan sombong—ketika ada dalam dirimu, kau merasa biasa saja. Namun, saat kau melihat sifat-sifat itu pada diri orang lain, kau segera menghindar dan merasa tersengat.
Tambah Rumi, “Seseorang tidak jijik pada kudis dan kurap di tubuhnya sendiri. Ia mencelupkan tangannya yang luka ke dalam sayur sop kemudian menjilatnya. Sama sekali tak muak. Namun, jika ia melihat kudis saja atau sekadar luka kecil di tangan orang lain, ia akan menghindari sop orang itu dan tidak mahu memakannya.
“Ketika sifat-sifat ‘buruk ibarat kudis dan kurap . Ketika kudis dan kurap itu ada di diri sendiri, seseorang tidak merasa menderita. Namun, jika ia melihat bekas-bekasnya saja pada orang lain, ia merasa tak nyaman dan perlu menghindari [menjauhinya].” (Jalaludin Rumi, Fihi Ma Fihi, hal.65) Jadi, apakah rasa sakit yang kita alami itu sama dengan rasa jijik orang lain melihat ‘penderitaan’ kita? Sesuatu yang cukup untuk kita ukurkan sikap dan peranan agamawan apabila sesuatu musibah melanda, dan belum melanda diri dan ahli keluarganya?
Pesan Rumi, “seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Jauhkan aib dari dirimu. Sebab, apa yang ada di diri saudaramu yang membuatmu tersengat juga ada di dirimu.”
Ya! Bagaimana mereka berpendirian bila masjid dan surau diperintahkan tidak berjemaah seperti sebelum COVID-19. Bandingkan apa pula pendapat mereka bila ada sekumpulan khairiah meninggal dunia dalam tempoh seminggu kerana ‘curi-curi berjemaah dalam gelap’ dan tidak mempedulikan orang lain, hadir juga ke surau atau masjid walaupun sudah ada gejala? Sedih juga bila satu keluarga di Kuala Brang, Terengganu dipulau kerana dijangkiti COVID-19, hingga untuk ke kedai pun seperti ‘dihina’ meskipun sudah disahkan pulih.
Atau bagaimana kita boleh belajar tentang ‘duka Memali’ yang terpaksa ditanggung oleh ahli keluarga yang kehilangan ketua keluarga hanya kerana mempertahankan ‘jihad politik’? Apa bantuan dan pertolongan yang mereka berikan, selepas ia tidak lagi memanas dengan tohmahan ‘zalim’, ‘taghut’ dan ‘tidak Islamik’? Apakah ketika itu tidak ada lagi ustaz atau agamawan mengulas, umat Islam tidak perlu takut kerana orang Islam sangat higenik, mengambil wudhu’ (membasuh tangan) lima kali sehari? Itu hanya kerana ingin memperlekehkan cadangan ‘basuh tangan’ berkali-kali kerana virus corona mungkin sedang bertenggek di bahagian kulit tangan.
Sekarang, sebahagian ulama (yang pernah mengisytiharkan kematian sebagai syahid) berada dalam tampok kekuasaan. Berapa besarkah ‘pengorbanan’ mereka terhadap pejuang-pejuang Memali yang melaksanakakan ‘seruan jihad’ itu telah mereka berikan? Apakah ia hanya sekadar ‘ingatan sejarah duka’, bukan sejarah untuk menata semula ideologi politik yang cukup “mendidihkan darah” itu?
Ya! Ia sudah menjadi sejarah, tetapi ia bukan fatamorgana. Ia realiti yang perlu setiap daripada manusia faham, sikap dan nilai agamawan yang menjurus kepada rasa ‘takjub’ dan membingkaikan taksub. Semuanya adalah senarai yang tidak boleh dipadam seperti juga kisah Umar Abdul Aziz, keadilan yang ditegakkan menjadi sebab untuk dibunuh, hanya kerana bersarangnya naluri tamak dan haloba.
Rumi turut bercerita mengenai orang Badwi yang bodoh dan pengikut-pengikutnya yang taksub. Juga perihal sebahagian masyarakat Islam mengambil sikap berdiam diri, tidak berusaha bangkit menentang kebejatan dan kebobrokan yang berleluasa dalam masyarakat. Pendirian sedemikian, menurut Rumi ‘merekalah sebenarnya kafir (walaupun Islam), kerana diam dan tidak berusaha menentang kebejatan itu.
Sifat kafir itu ada dalam diri, dan sukar untuk dihapuskan walaupun dengan racun mahupun diberikan penawarnya. Sifat kekafiran yang abadi, jiwa telah membusuk dan terimalah penghakiman (balasan) di hari perhitungan (akhirat) nanti.
Jalaludin Rumi mengingatkan: seseorang akan menjadi sangat hina bila nafsunya digunakan untuk memperdayakan orang lain dengan ungkapan “Tuhan Itu Maha Pengampun”, yakni berbuatlah apa pun (sesuatu yang salah) kerana Tuhan Itu Maha Pengampun. Menjadikan diri seperti Qabil dengan sengaja, kerana Tuhan Maha Pengampun. Manusia sebenarnya meletakkan diri sendiri “dalam kemusnahan”.
Semoga terpelihara daripada ‘kemusnahan’: hati, perasaan, jiwa dan perilaku. Kehidupan sekarang (di dunia) adalah satu kaedah bagaimana Allah SWT menyuruh kita melatih diri (belajar) :1) memahami makna kehidupan dan kematian; (2) meningkatkan keimanan (ketakwaan); dan (3) amalan yang baik dan berkualiti (Achmad Chodjim, Membangun Syurga, hal.40-45) manakala (Jalaludin Rumi, Fihi Ma Fihi, hal. 370) kehidupan manusia akan lebih hebat jika disaluti oleh Cinta: Cinta Tuhan kepada Manusia; Cinta Manusia Kepada Tuhan; dan tidak terlampau ghairah bercinta antara sesama manusia jangan pula terlupa bahawa “Manusia cenderung pada dunia lain. Ketika ia condong pada jalan sebaliknya, yakni pada dunia yang lebih rendah, itu menandakan ‘cangkir’ telah hilang di balik hijab.”
‘Hidup ini akan penuh kepedihan dan penderitaan bila kita bersanding dengan para provokator yang sewaktu-waktu menyalakan api’ sambung Achmad Chodjim, “tanpa menggarap dunia dengan benar, bagaimana kita bisa ke syurga?. Tanpa menanam bagaimana kita dapat mengetam?”. Maknanya, bagaimana ‘hendak ke syurga’ kalau hidup di dunia bergelumang dengan perilaku yang merosak dan menghancurkan keharmonian sarangnya?
Ya! Di Syurga tetap ada bidadari. Jelas Allah SWT dalam firman-Nya yang bermaksud: “Dan (mereka dilayani) bidadari-bidadari yang cantik parasnya, Seperti mutiara yang tersimpan dengan sebaik-baiknya.” (al-Waaqiqh, ayat 22 -23)
Bidadari diciptakan di syurga untuk menemani kehidupan orang yang semasa ‘di dunia’ hidupnya mementingkan agama. Abu Hurairah RA meriwayatkan bahawa Rasullullah SAW bersabda: “Kalau kamu ingin memiliki bidadari di syurga, antara caranya ialah peribadikanlah dirimu dengan akhlak yang baik. Orang yang paling dekat denganku pada hari akhirat nanti ialah orang yang memperelokkan akhlak di atas dunia ini.”
Ya! Untuk hidup dengan akhlak yang baik, elakkan diri daripada bercakap keji, menyebarkan fitnah, mengadu-domba, berkelakukan buruk dan berburuk sangka. Itulah sebabnya Allah SWT memberikan ganjaran iaitu didampingi oleh bidadari kepada mereka berkelakuan baik dan berakhlak mulia. Alangkah ruginya nanti, jika semasa hidup tidak berkelakuan baik dan berakhlak mulia, termasuk bila ada agamawan bertentangan perilaku dan apa yang diucapkan, juga bukan agamawan yang sentiasa ‘menyalakan api permusuhan dan sengketa’.
Biarpun bukan ‘agamawan’, mudah-mudahan kita dijauhkan dari terjerumus ke ‘bakul sampah agama’. Semoga kita termasuk dalam kalangan ‘orang yang mengenal diri sendiri’ dan menyedari bahawa destinasi akhir ‘perjalanan’ ialah menuju ke ‘Jalan Yang Benar’, bukan berkedok taksub dan materialistik. Hidup sederhana yang disinari cahaya keimanan dan jalan taqwa. In Sya Allah.
KAMARUN KH


Recent Comments