Dalam alam sekular, politik dianggap sekadar seni untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan, dengan segala cara. Politik harus dibebaskan dari moralitas. Yang penting kekuasaan.
Demi meraih kuasa, tipu sana tipu sini, bukan soal lagi. Bahkan, jika perlu, teror pun digunakan, demi kekuasaan. Pertahankan dan rebut kekuasaan, dengan cara apa pun!
Itulah politik bebas nilai, sebuah bentuk politik yang secara sistematis diteorikan oleh Niccolo Machiavelli. Politik dibebaskan dari nilai-nilai moral dan agama. Dalam sejarah pemikiran politik, nama Machiavelli memang monumental. Oleh para pemikir di Barat kemudian, karya Machiaveli, The Prince, dianggap memiliki nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh besar dalam sosial politik umat manusia.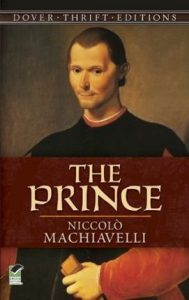
Machiavelli dianggap sebagai salah satu pemikir yang mengajak penguasa untuk berpikir praktis demi mempertahankan kekuasaannya, dan melepaskan nilai-nilai moral yang justru dapat menjatuhkan kekuasannya. Karena itu, banyak yang memberikan predikat sebagai “amoral”. Tujuan utama dari suatu pemerintahan adalah “survival” (mempertahankan kekuasaan).
Kata Machiavelli, “Jika situasi menjamin, penguasa dapat melanggar perjanjian dengan negara lain, dan melakukan kekejaman dan terror.” Ditulis dalam The Prince: “It is necessary for a prince, who wishes to maintain himself, to learn how not to be good, and to use this knowledge or not use it, according to the necessity of the case.” Yang terpenting dari pemikiran Machiavelli, adalah ia telah mengangkat persoalan politik dari aspek moral dan ketuhanan.
Jadi, nilai penting dari pemikiran Machiaveli adalah usahanya melepaskan pemikiran politik dari kerangka agama dan meletakkan politik semata-mata urusan ilmuwan politik. Apa yang dilakukan Machiaveli yang kemudian disebut sebagai “politik modern” tentu saja tak lepas dari arus besar renaissance (kelahiran kembali) masyarakat Eropa, yang selama hampir 1.000 tahun hidup di bawah sistem politik teokrasi (kekuasaan Tuhan). Tuhan – melalui wakilnya di bumi – mendominasi segala aspek kehidupan, termasuk politik. Pemerintahan dianggap tidak sah, jika tidak disahkan oleh wakil Tuhan.
Berbagai penyimpangan sistem teokrasi kemudian melahirkan semangat pemberontakan terhadap agama. Revolusi Perancis (1789) yang mengusung jargon “Liberty, Egality, Fraternity”, secara terbuka menyingkirkan – bukan hanya sistem monarki – tetapi juga dominasi kaum agamawan dalam politik.
Sebelumnya, para agamawan (clergy) di Perancis menempati kelas istimewa bersama para bangﷺan [sic, bangsawan]. Mereka mendapatkan berbagai hak istimewa, termasuk pembebasan pajak (cukai). Padahal, jumlah mereka sangat kecil, yakni hanya sekitar 500.000 dari 26 juta rakyat Perancis.
Trauma pada dominasi dan hegemoni kekuasaan agama itulah yang memunculkan paham sekularisme dalam politik, yakni memisahkan antara agama dengan politik. Mereka selalu beralasan, bahawa jika agama dicampur dengan politik, maka akan terjadi “politisasi agama”; agama haruslah dipisahkan dari negara. Agama dianggap sebagai wilayah peribadi dan politik (negara) adalah wilayah publik; agama adalah hal yang suci sedangkan politik adalah hal yang kotor dan profan.
*****
Di Eropa, trauma sistem teokrasi kemudian memunculkan tradisi politik sekular-liberal. Fenomena ini sebenarnya tidak terjadi dalam dunia Islam. Kaum Muslim selalu melihat politik sebagai bahagian dari agama. Politik adalah ibadah. Tujuan utama politik adalah untuk menyebarkan kebenaran, dan menjaga agama melalui kekuasaan. Karena tujuannya mulia, maka cara yang digunakan pun harus mulia pula. Tujuan tidak menghalalkan segala cara.
Pengalaman sejarah dan trauma Barat terhadap hegemoni sistem teokrasi mengharuskan dilakukannya sekularisasi di Barat. Tetapi, Islam tidak mengalami hal semacam itu. Islam tidak mengenal sistem teokrasi dan tradisi Inquisisi. Bernard Lewis, professor di Princeton University mengakui, bahawa kaum Muslim memang tidak mengembangkan tradisi sekular dalam sejarah mereka.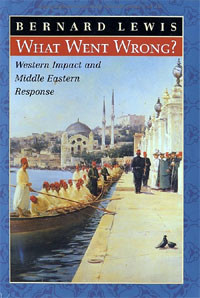
Bahkan, kata Bernard Lewis, kaum Muslim akan selalu menentang keras tradisi sekular tersebut. Ini berbeda dengan tradisi Kristen di Barat. “From the beginning, Christians were taught both by precept and practice to distinguish between God and Caesar and between the different duties owed to each of the two. Muslims received no such instruction,” tulis Lewis dalam bukunya, What Went Wrong? Western Impact and Middle Eastern Response, (London: Phoenix, 2002).
Karena itu, memang, sejatinya, politik sekular dan liberal, apalagi politik ‘machiavellis’ harusnya tidak dikenal dalam tradisi Islam. Begitu juga dalam tradisi politik di Indonesia yang mendasarkan diri kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Allah SWT) bukan sekedar mengakui “ada-Nya”, tetapi juga harus mengakui kedaulatan Tuhan Yang Maha Esa. Yakni, kerelaan manusia untuk diatur oleh Allah SWT.
Karena itulah, berpolitik dalam Islam adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Di antara tujuh golongan yang akan mendapatkan perlindungan di Hari Akhir, adalah pemimpin yang adil. Pemimpin dengan kekuasaan di tangannya berpeluang mendapatkan pahala yang besar.
Jadi, sangatlah merugi jika politik hanya berhenti kepada dimensi duniawi saja. Jargon, “Kekuasaan untuk kekuasaan”, adalah jargon sekular. Dalam pandangan Islam, “Politik adalah untuk ibadah”; Politik bukan hanya sekedar berebut kekuasaan. Wallahu A’lam bish-shawab. (Depok, 24 Juni 2021).*
Sumber: Dr. Adian Husaini, https://www.hidayatullah.com/


Recent Comments