Seratus tahun selepas kematian al-Ghazali (1058-1111 M) muncul pula seorang ahli sufi yang cukup zuhud dan bervisi dalam memperkatakan tentang hidup dan kehidupan. Jalaludin Rumi (1207-1273 M), sangat mengingati pesanan gurunya, Shams-i Tabrizi (1185-1248 M): “Setiap kerosakan yang terjadi di dunia ini berlaku kerana seseorang percaya kepada seseorang yang lain atas dasar taksub, atau dia menafikan sesuatu kebenaran juga atas dasar taksub.”
Hal ini mengingatkan sebahagian daripada umat Islam apa yang pernah dikategorikan oleh al-Ghazali mengenai empat jenis manusia yang ada di muka bumi.
Pertama, Rojulun Yadri wa Yadri Annahu Yadri (Seseorang yang tahu (berilmu), dan dia tahu kalau dirinya tahu).
Kedua, Rojulun Yadri wa Laa Yadri Annahu Yadri (Seseorang yang tahu (berilmu), tapi dia tidak tahu kalau dirinya tahu).
Ketiga, Rojulun Laa Yadri wa Yadri Annahu Laa Yadri (Orang yang tidak tahu dan mengetahui bahwa ia tidak tahu).
Keempat, Rojulun Laa Yadri wa Laa Yadri Annahu Laa Yadri (orang yang tidak tahu dan tidak mengetahui bahwa ia tidak tahu).
Kategori pertama merupakan manusia yang paling baik, dia tahu bagaimana untuk memanfaatkan ilmunya untuk kepentingan ramai dan sentiasa berfikir untuk membaiki kesilapan, sentiasa meletakkan ilmunya sebagai jalan mendapatkan keredhaan Allah SWT, bukan kepentingan diri.
Kelompok kedua ini memang banyak kita temui dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi sayangnya tidak mempraktikkan ilmunya untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam istilah moden, orang sedemikian lebih bersifat teori dan berfikir dalam situasi yang sangat ideal. Oleh kerana itulah dari segi tindakan tidak ada yang dilakukannya, kecuali berfalsafah dan berteori. Inilah ciri-ciri agamawan yang hebat berkata-kata, tetapi, kehidupan kesehariannya seumpama ‘harimau tidur’.
Kelompok ketiga adalah mereka yang sedang mencari ilmu. Menurut al-Ghazali, orang dalam kategori ini masih dianggap baik, kerana memahami kekurangan diri dan berusaha mengatasinya, dan bersungguh-sungguh melakukannya.
Kategori keempat, ialah mereka yang paling buruk atau tidak berguna kepada dirinya sendiri dan juga orang lain – bodoh sombong – dan dalam kesehariannya melihat diri sendiri ‘sentiasa tahu’, maka akibatnya, sentiasa menyalahkan ‘orang lain’ di atas kelemahan ilmu pengetahuannya.
BACA JUGA: AGAMAWAN DAN “BAKUL SAMPAH AGAMA”, https://omiw.com.my/Web/2021/06/16/agamawan-dan-bakul-sampah-agama/
Saya temui sangat banyak manusia kategori keempat ini dalam cetusan kemarahan dan pendapat sepanjang naratif pandemik COVID-19, hampir setiap hari ada posting mereka. Ada yang bercakap mengenai ‘keburukan vaksin’, maka dikaitkan pula sebagai satu bentuk ‘konspirasi’. Pengambilan vaksin tidak sepatutnya diterima oleh umat Islam. Bagi menakutkan ramai orang, maka diselitkan cerita penerima vaksin ‘hilang akal’, ‘meninggal dunia’, dan paling lucu ialah bantahan seorang perempuan, akibat ‘vaksin kedua menaikkan libido (seks) lelaki’ atau ‘memanjangkan saiz kemaluan’. Ia mungkin menyebabkan ‘keselesaan perempuan’ tercabar.
Beberapa hari lalu, ada satu lagi ‘rasa kesal’ kenapa perlu bergantung kepada bukan Islam dalam penghasilan vaksin. Penyoal itu rasanya ikut terseret dengan ‘emosi benci’ terhadap orang lain, dirinya tidak cuba memasuki kategori ketiga, dan untuk berada di kategori pertama, ia terlalu jauh.
Sepatutnya sebelum memberikan kenyataan tersebut, telitilah apa yang berlaku dalam kalangan umat Islam seluruh dunia. Sejak runtuhnya empayar-empayar Islam selepas Perang Dunia I, yakni jatuhnya Empayar Uthmaniyyah, umat Islam berengsot kepada ‘kebekuan intelektual’ dan kemunduran. Lebih ramai umat Islam bersedia bersengkongkol dengan kuasa barat, dan hanyut dalam nilai-nilai peradaban yang sangat menitikberatkan kepada materialisme. Tujuan mencari ilmu juga sudah berubah, bukan untuk menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat, tetapi mendapatkan keuntungan peribadi atas nama kerjaya, profesional dan sebagainya.
Akibatnya, perkembangan ilmu pengetahuan umat Islam tercorot, tidak lagi dapat melahirkan pemikir-pemikir yang hebat dan pakar yang cukup berpengaruh. Umat Islam tidak lagi dilihat sebagai pencetus ilmu-ilmu yang sangat diperlukan oleh manusia sejagat. Umat Islam kembali kepada pemikiran jumud dan anti ilmu-imu muamalat, menyingkirkan kepentingan pengisian jiwa dan rohani.
Kalaupun ada, kemunculan mereka hanyalah sekadar mengulangi apa yang sudah ditemui oleh orang lain, dan lebih berminat dalam kajian bersifat ‘awalan’, bukan kajian yang mencetuskan teori baharu yang lebih baik serta bersesuaian dengan semangat zaman dan kehendak agama. Mereka menjadi pakar, pakar yang hanya berpengetahuan tetapi tidak mampu menyelesaikan masalah umat.
Kajian mereka sangat bersifat ‘initial’ atau permulaan, dan bagi Zainudin Sardar, situasi seperti ini disifatkan belum memasuki fasa jihad intelektual. Jika pun ada, hanya muncul beberapa orang, tetapi saha dan perjuangan mereka sangat mudah dipatahkan. Pola pola pemikiran dan analisisnya sangat terhad, hanya bersandarkan sampel yang kecil dan tidak menyeluruh. 
Tahun 1980-an kita disejukkan dengan gerakan Islamisasi Ilmu. Ramai yang bercakap mengenainya, tetapi, kerangka Islam yang benar-benar Islamik belum juga muncul sampai sekarang. Beberapa tahun kebelakangan ini, muncul pula kesedaran untuk menghidupkan kembali kerangka ilmu-ilmu Islam berdasarkan model klasik.
Sayangnya, visi dan pendekatannya sekadar mengulangi model klasik, tidak diterjemahkan dalam kerangka yang lebih baik dan komprehensif. Sepatutnya, bila sesuatu pendekatan baharu atau inovasi yang hendak diperkenalkan, ia adalah lebih baik daripada sebelumnya, bukan sekadar menutup “kebocoran perjalanan” untuk mencipta peradaban baharu. Bukan hanya sekadar menterjemahkan kitab-kitab klasik dengan mengekalkan bahasa klasik, ia sepatutnya diterjemahkan dalam konteks bahasa semasa dan diberikan anotasi sepadan.
Akibat sekadar ‘menutupi kebocoran’ itulah sistem pendidikan di Malaysia terarah kepada membina indeks dan memposisikan kedudukannya dalam kelompok tertentu dalam ‘ranking antarabangsa’. Bukan sedikit tenaga, wang, masa dan keringat dicurahkan , walhal kita sedar, tujuan akhir pendidikan itu adalah ‘kemenjadian murid’, bukan mengejar ‘ranking’ dan ikut berorientasikan ‘keperluan pasaran’. Sebab itulah semakin bertambah penganggur berijazah, kerana dasar pendidikan tidak mampu menyelesaikan persoalan asas, untuk apa seseorang itu belajar. Kita tidak diajar bagaimana menggunakan ilmu untuk ‘membentuk kehidupan’ tetapi kita diasak memburu kerjaya yang akhirnya menjadi hamba budaya kapitalisme.
Kita sepatutnya bersaing membentuk sistem pendidikan yang tidak kosong spiritual, melahirkan pakar yang cukup kuat daya Sekarang kami difitnah netizen satu Malaysia. Penduduk kena fitnah, masjid kena fitnah, Zakat Kedah kena fitnah, kerajaan (negeri) kena fitnah, tuan tanah pun kena fitnah angkara kuasa viral sebelah pihak. Bukan membesarkan kumpulan pengguna dan pengikut yang takjub dan taksub kepada nilai-nilai konsumerisma, budaya yang memang menjadi acuan dan keperluan sistem peradaban yang sakit. Sebab itulah ada fenomena ‘enam hari seminggu menghabiskan masa memodelkan bank bagaimana mencipta keuntungan’, hanya ‘sehari ke gereja’ seperti pernah diperkatakan oleh John Genter, seorang wartawan Amerika Syarikat. Saya kutip pandangan itu daripada petikan Profesor Dr Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya, Islam Teras Peradaban Masa Depan, (terjemahan Arsil Ibrahim), terbitan Institut Terjemahan Negara Malaysa (ITNM), 1998, hal.14),
Kita tahu, salah satu vaksin terawal dan diproses dengan kaedah termoden (kaedah MRNA) dihasilkan oleh pasangan doktor keturunan Turki yang beragama Islam, tetapi menetap di Jerman. Ia merupakan inovasi yang dilakukan oleh Dr Ugur Sahin dan isterinya, Dr Ozlem Turci, di makmal penyelidikan kepunyaan mereka, BioNTech. Sebagaimana yang kita ketahui, untuk membuat penyelidikan, ia memerlukan biaya yang besar, dan kumpulan penyelidik yang dedikasi. Begitu juga untuk memasarkannya, ia memerlukan rangkaian yang cekap dan kepakaran yang bukan sekadar mampu menghasilkan produk. Ini tidak dimiliki oleh umat Islam, belum muncul lagi organisasi pemasaran dan perdagangan yang cukup hebat sejak kehebatan pedagang-pedagang Islam dikembirikan oleh kuasa penjajah Eropah (Portugis, Belanda, Sepanyol, Perancis dan British).
Itulah yang kita lihat, kelemahan yang ketara dalam masyarakat Islam secara universal. Kita tahu, ada cerita kehebatan seseorang pengamal perubatan trasisional menghasilkan formula menyembuhkan penyakit. Tetapi sayangnya, formulanya tidak dikembangkan kepada penyelidikan yang lebih dipercayai, termasuk ujian makmal dan alahan yang boleh membantu penggunanya berhati-hati sebelum megambilnya. Dengan mengetahui ‘alahan’ atau ‘kesan sampingan’ ia dapat membantu pengguna yang bermasalah mencari solusi (cara mengatasi), bukan sekadar cukup dengan janji ‘wang dikembalikan’. Wang dikembalikan ‘jika tidak berkesan’, tetapi bagaimana jika ‘berhadapan dengan kesan memudaratkan’.
Wang tidak ada apa ertinya lagi dalam keadaan kesan sampingan (alahan) telah menimbulkan kemudaratan yang fatal. Adakah ketika pengguna dalam keadaan ‘kritikal’ atau kegagalan fatal, pengamal perubatan tradisional itu sedia bertanggungjawab? Ini adalah persoalan yang patut dipertimbangkan dan menjadi asas yang sangat kritikal kerana sebelumnya sangat percayakan ‘mujarab’nya kaedah perubatan tradisional tersebut. Berapa ramai yang sanggup mengheret ‘salah ubat’ ke muka pengadilan? Ia berbeza dengan perubatan moden. Syarikat yang mengeluarkannya boleh didakwa, dan pihak yang memberikan kelulusannya akan dipertanggungjawabkan. 
Saya kadangkala menjadi sedikit ‘marah’ apabila ada pihak yang menggunakan agama untuk menjual ‘penawar’ atas alasan ‘makanan tambahan’ . Mereka mendakwa, cukup berkesan: Daripada yang tidak mampu berdiri, boleh bersembahyang berdiri. Ia ditempel dengan gambar dan testimoni. Saya kadangkala khuatir, apakah testimonial itu cukup jujur? Apakah testimonial itu seumpama ‘testimonial Zara Zya’ yang cukup ‘geli’ dan ‘tidak tahu malu’. Belum berkahwin tetapi mempromosikan produk dalam mencetuskan keintiman ‘pasangan’. Mengapa dipertahankan ‘pembohongan’ tersebut dan jika mengambil perspektif al-Ghazali di manakah posisi itu, kategori ke berapa?
Saya kembali kepada Maulana Jalaludin Rumi. Beliau memerihalkan bahawa golongan beragama (agamawan) boleh memberikan kesan besar kepada kehidupan peribadi seseorang dan juga kerukunan hidup bermasyarat. Kesannya, adalah dua, kesan positif dan kesan negatif. Kesan negatif berlaku apabila situasi kehidupan rosak, peribadi manusia penuh dengan pelbagai perilaku buruk, bermusuhan dan sentiasa bersengketa.Ia berpunca kepada maklumat yang salah, pengetahuan yang buruk dan tidak berfaedah. Dalam sebuah kumpulan ajaran dan syarahannya, Fihi Ma Fihi, dikatakan berlaku kerana sifat dan sikap taksub. Ia dimulakan oleh ulama buruk atau jahat (suu’). Apabila sikap taksub menguasai seseorang, tiada lagi keputusan dibuat berdasarkan cetusan akal yang sihat sebaliknya, setiap alasan hanya bersandarkan apa yang difahaminya dalam kerangka pengetahuan yang buruk itu.
Setiap alasan yang diberikan, disusuli dengan pernyataan hukum yang cukup tegas dan tidak munasabah, jauh daripada asas-asas kebenaran. Misalnya, disebabkan taksub dengan ideologi politik tertentu, maka jika tidak berada atau menyokong perjuangan parti politik berkenaan, ia akan dihukum kafir walaupun hakikatnya, seseorang itu tidak berada dalam keadaan syirik. Keimanannya tetap teguh: sembahyang berkiblatkan Masjidil Haram; bersyahadah dengan lafaz “Tiada Tuhan Selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah Pesuruh Allah”; menghafal dan menjadikan al-Qur’an sebagai petunjuk dan sunnah sebagai ikutan; tidak meninggalkan sembahyang lima waktu sehari semalam; dan sebagainya. Cuma berbeza ialah tidak menyokong parti politik berkenaan? Apakah sikap sedemikian dianggap terkeluar daripada akidah?
Itulah juga bila mendakwa mereka yang mengambil vaksin bagi melindungi diri dan orang lain daripada jangkitan COVID-19 dituduh lebih percayakan vaksin daripada ketentuan Allah SWT. Mereka yang mengambil vaksin ‘haram’ kerana memasukkan ke dalam diri (tubuh bahan) bahan-bahan yang diragui status halalnya. Vaksin juga bukan penentu seseorang itu tidak mati. Cukup mudah dakwaan segelintir ‘agamawan’ sehingga ada yang berkata, ia adalah haram dan sesuatu yang haram itu bila diambil boleh dianggap melakukan dosa besar. Cukup dengan tafsiran dan hujah. Sebenarnya, agamawan itu sendiri belum cukup pengetahuan dan sandaran ilmunya.
Dalam sesebuah negara, perkara-perkara yang tidak ada hukumnya dnegan jelas, keputusannya adalah berdasarkan ijtihad pada pakar yang berpengetahuan, termasuk agamawan. Setiap daripada mereka berkumpul. berbincang dan berbahas sebelum mencapai kata sepakat. Dalam hal pengambilan vaksin, fatwa sudah jelas bahawa ia dibolehkan atas keperluan maslahat. Jika ada unsur-unsur yang diragui digunakan sebagai bahan pembuatan vaksin, ia dikategotikan sebagai makruh. Ertinya, boleh diambil dan tidak dikategorikan sebagai berdosa.
Vaksin bukan ubat, ia adalah ikhtiar untuk meningkatkan imuniti seseorang. Maka, ia adalah keperluan, bukan bermakna menyekat daripada mati. Mati tetap akan hadir dalam setiap makhluk yang bernyawa. Vaksin berdasarkan kebolehpercayaannya sudah direkodkan antara 60 hingga 95 peratus. Maknanya, kesan positinya adalah lebih besar. Itu adalah ‘kebenaran yang dibuktikan secara sains’, biarpun dianggap sebagai sementara, ia cukup menyakinkan. Cuba fikirkan secara terbalik, tanpa vaksin hanya 5 hingga 40 peratus sahaja seseorang itu tidak dijangkiti oleh virus. Jika dalam dua perspektif ini dibandingkan, apa fakta yang boleh menyakinkan anda dan membantu membuat keputusan.
Tentunya, sebagai manusia kita akan melihat perkara-perkara positif itu terlebih dahulu, jika peratusannya lebih besar berbanding negatif, kita akan membuat keputusan yang saksama. Bukan keputusan berbentuk spekulatif. Sebahagian besar agamawan lebih gemar membuat tafsiran yang bersifat spekulatif, berdasarkan sudut pandangan dan tahap ketaksubannya. Inilah menyebabkan sebahagian daripada umat Islam terkongkong dan mudah terpengaruh dengan pelbagai bentuk doktrin. Doktrin yang cukup merosakkan. Dalam istilah dinamik psikologi, boleh dipanggil jumud ataupun minda tertutup. 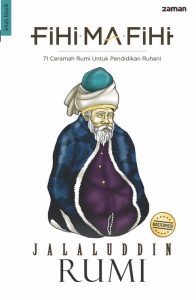
Begitulah, jika dalam hidup ini kita sering bercakap tentang keburukan dan hal-hal yang negatif, sampai bila pun kita tidak bahagia dalam hidup dan suasana kehidupan sentiasa dalam iklim yang negatif, dan tidak berkembang. Kita hidup sebagai makhluk bersosial, maka, sesuatu yang positif itu wajar diberikan keutamaan dalam menyusun perilaku dan tindakan, dan sekaligus menolak sahaja yang bersifat negatif. Dalam kehidupan bekerkeluarga misalnya, Islam melarang setiap orang menceritakan perihal pasangan masing-masing di depan orang lain, kerana apa? Negatifnya lebih besar, mudaratnya lebih membuak-buak sehingga menimbulkan emos marah dan konflik –saling menyalahkan, bukan saling mencari penyesuaian, membaiki kelemahan dan membentuk persefahaman. Kasih sayang itu lahir daripada persefahaman dan saling menghargai.
Dalam tutur kata, ada masalahnya, seperti kata Rumi: “Kata-kata hanya perantara. Yang memunculkan ketertarikan seseorang dengan orang lain ialah unsur kesesuaian – bukan kata-kata. Bahkan, jika seseorang melihat ratusan ribu mukjizat atau karamah pada diri nabi atau wali, namun tidak ada kesesuaian itu tiada gunanya. Unsur kesesuaian itulah yang membuat seseorang berghairah dan gelisah.”Jalaludin Rumi, Fihi Ma Fihi: 71 Ceramah Rumi Untuk Pendidikan Ruhani, (terjemahan), Jakarta: Penerbit Zaman, 2016, hal.36). (Bersambung)
KAMARUN KH

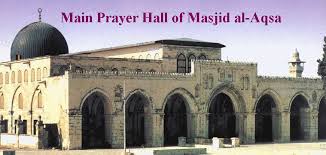
Recent Comments